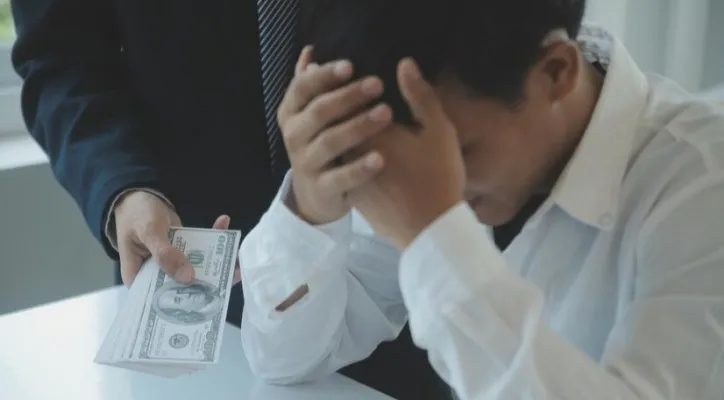Dengan tradisi akademis yang begitu kuat diseputar kelahiran Pancasila, tantangannya berada pada tataran praksis. Di sini diperlukan disiplin, semangat, tekad, dan program agar keseluruhan esensi filsafati yang terkandung dalam Pancasila dapat dijalankan. Mengapa tradisi akademis penting?
Sebab di situlah nalar dikedepankan. Terlebih dalam kebijakan publik. Rasionalitas dalam setiap kebijakan publik diambil atas dasar potret sosial yang seharusnya dicermati secara obyektif, bukan didasarkan pada kepentingan jangka pendek kekuasaan. Ketika lapisan masyarakat bawah menderita akibat kenaikan BBM misalnya, bagaimana kajian akademis menilai kebijakan tersebut?
Realitas obyektif atas kenaikan BBM seharusnya dijawab dengan kebijakan meningkatkan kemampuan produksi rakyat, bagaikan peribahasa ”berikan kail, jangan ikannya”. Di sini pendidikan vokasi, penguatan UMKM dengan modal kerja, penguatan akses pasar, dan peningkatan kualitas produk dll dapat dikedepankan.
Namun ketika rasionalitas kekuasaan lebih dominan, apalagi menjelang Pemilu, muncul godaan kebijakan bantuan jangka pendek yang hanya sekedar mendorong konsumsi. Disinilah daya kritis melalui kajian akademis bisa mempertanyakan tepat tidaknya suatu kebijakan.

Ilustrasi. (ucha)
Tradisi akademis akan melahirkan research based policy (RBP), dimana kebenaran ilmiah dikedepankan. RBP ini menjadi rel kebijakan publik agar apa yang diamati sebagai masalah, meski baru muncul sebagai fenomena, bisa dipahami dalam konstruksi yang lebih besar dalam kaitannya dengan sistem sosial, sistem produksi nasional, bahkan berkaitan dengan kebijakan strategis suatu negara.
Jawaban atas realitas mengapa petani miskin oleh Bung Karno dikonstruksikan pada persoalan sistem perekonomian yang menghisap. Petani miskin akibat penghisapan sistem kapitalisme. Dalam sistem ini petani hanya menjadi salah satu elemen dalam sistem produksi yang menguntungkan pemegang modal.
Solusi yang diambil Bung Karno adalah membangunkan rakyat indonesia agar memiliki kesadaran kolektif sebagai bangsa terjajah. Kesadaran ini melahirkan energi perjuangan untuk merdeka. Di seberang “Jembatan Emas kemerdekaan” itulah para pemimpin bangsa bertekad untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Di sinilah prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dikedepankan.
Dalam era saat ini, ketika sistem demokrasi dan sistem ekonomi dalam prakteknya berubah menjadi liberal, setiap ada fenomena seperti trend kenaikan harga beras, rasionalitas publik dikerdilkan dengan “pembenaran nalar” tentang pentingnya impor. Alih-alih mencari akar persoalan mengapa Indonesia selalu tergantung pada impor pangan global, yang terjadi hanyalah manipulasi nalar publik, bahkan sering dibumbui dengan klaim “kebenaran akademis” untuk melegitimasi impor.
Atas dasar hal tersebut, tradisi ilmiah yang mengedepankan kebenaran obyektif bisa menjadi tolok ukur analisis kebijakan. Kebijakan bisa dievaluasi secara obyektif dari landasan kebijakan; korelasi dengan ideologi Pancasila, amanat konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan juga bisa dilihat dari komitmen dan moralitas pemimpin bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dalam tradisi ilmiah tersebut bagaimana watak, karakter, keberpihakan, dan tanggung jawab seorang pemimpin bagi masa depan bisa dikaji secara obyektif.
Jadi sungguh mengherankan, ketika sosok senior seperti Bung Saur M. Hutabarat hanya melihat kajian kepemimpinan strategis para pemimpin negara, khususnya Presiden, dari perspektif politik semata, hanya karena lontaran gagasan tersebut disampaikan oleh seorang politisi. Kajian akademis apapun namanya, menjadi tidak obyektif ketika modus politiknya untuk mendiskreditkan pihak lain.
Tradisi ilmiah menghilangkan prejudice. Namun tradisi akademis tidak bisa membutakan diri dengan budaya bangsa, seperti “mikul duwur mendem jero” atau tradisi kritik sebagai bangsa timur. Tradisi ilmiah juga bisa mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan persoalan seperti misalnya apa yang menyebabkan seorang pemimpin dikatakan berhasil; bagaimana model kepemimpinan strategis yang cocok untuk bangsa indonesia; apa kriteria kepemimpinan strategis yang diambil dari model keberhasilan para Presiden Republik Indonesia?
Jadi perbandingan antara kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto misalnya berkaitan dengan bagaimana membangun kekuatan pertahanan TNI yang profesional, modern dan disegani di dunia internasional dapat saja dilakukan secara akademis. Kajian kepemimpinan antara Pak Harto dan Bu Megawati di dalam mengatasi krisis multi-dimensi juga dapat dilakukan secara obyektif.