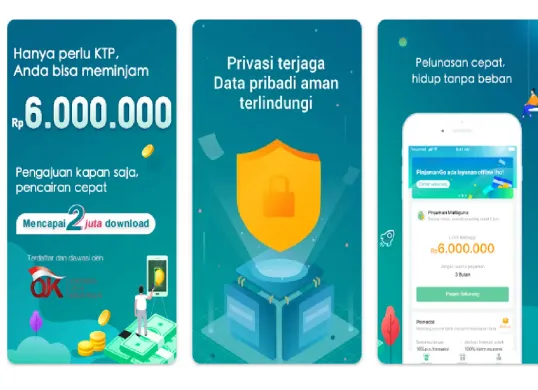“Pejabat yang langsung dipilih rakyat, mestinya lebih amanah. Bukan menggunakan kekuasaannya, mengelabui rakyat untuk memperkaya diri sendiri” – Harmoko.
Biaya politik mahal, tidak terbantahkan lagi.
Menjadi kontestan dalam pilkada perlu dana besar, sedikitnya Rp30 miliar untuk maju sebagai calon bupati.
Calon gubernur, perlu menyiapkan Rp100 miliar.
Pastinya angka tersebut adalah minimal guna memenuhi kebutuhan dasar (biaya resmi) seperti kampanye, kebutuhan logistik penunjang kampanye, dan saksi.
Belum lagi biaya tidak resmi seperti mahar politik dan money politics yang jumlahnya relatif variatif.
Semakin luas cakupan wilayah dan jumlah penduduknya serta kian tinggi potensi sumber pendapatan daerahnya, akan bertambah mahal biaya politik yang dikeluarkan.
Seorang pimpinan parpol besar pernah mengatakan biaya membayar saksi di daerah lumbung suara, mencapai miliaran rupiah.
Di wilayah Jawa misalnya, digelontorkan lebih dari Rp10 miliar untuk membayar saksi guna memastikan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS berjalan adil.
Jika setiap provinsi minimal terdapat 100.000 TPS, setiap TPS dijaga 1 saksi dengan honor Rp300 ribu, maka didapat angka Rp30 miliar.
Mestinya dana sebesar itu dapat dipangkas, jika kader parpol yang mengawal pilkada mulai dari TPS hingga hasil akhir.
Akan terjawab, kalau mesin parpol dapat bergerak sebagaimana diharapkan, dan kaderisasi dalam pemilihan terstruktur secara rapi.
Politik berbiaya tinggi akan melahirkan perilaku korupsi.
Ini hasil kajian, juga pengakuan sejumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data KPK menyebutkan hingga kini terdapat 429 kepala daerah hasil pilkada yang terjerat korupsi.
Data lain mengungkap sepanjang semester I tahun 2021, sudah 10 kepala daerah (1 gubernur, 2 walikota dan 7 bupati/wakil) yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Dari pengakuan sejumlah kepala daerah yang tertangkap tangan, korupsi untuk mengembalikan secara cepat biaya politik yang telah dikeluarkan.
Biaya politik mahal melahirkan kebijakan transaksional seperti jual beli kursi jabatan bergengsi, misalnya kepala dinas.
Cara paling mudah dan cepat mendapatkan uang.
Hanya dengan mengandalkan gaji, pastinya tidak akan tercukupi. Sebut saja gaji bupati Rp6,5 juta plus uang prestasi dan tunjangan lain – lain di daerah makmur dengan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) di atas Rp7,5 triliun, sehingga total pendapatan per bulan sebut saja Rp100 juta, maka setahun Rp1,2 miliar.
Lima tahun Rp6 miliar, masih jauh dari modal yang dikeluarkan untuk menjadi bupati. Tentang hartanya, sulit juga karena kekayaan yang dilaporkan tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Tak heran, kekuasaan kepala daerah sering tergadaikan karena biaya pemilihan disponsori dulu oleh pihak ketiga alias "ngutang".
Hasil penelitian KPK terungkap lebih 80 persen calon kepala daerah dibiayai pihak ketiga, tentu dengan komitmen.
Setelah terpilih akan memenuhi apa yang diminta oleh penyandang dana, entah itu terkait proyek atau kebijakan tertentu yang menguntungkan investor pilkada.
Jika sudah demikian, apa yang dapat diharapkan dari kepala daerah hasil pilkada langsung.
Memajukan daerah atau malah memundurkan?
Apa solusinya?
Soal ini akan saya singgung pada “Kopi Pagi" sesi berikutnya.
Dampak lain dari pemilihan langsung seperti dikatakan pak Harmoko lewat kolom “Kopi Pagi"-nya menjadikan para pemimpin terpilih bagaikan menjelma menjadi “Raja Kecil“ baru di wilayahnya.
Bupati tidak sungkan pada gubernur, karena bupati dipilih langsung oleh rakyatnya, bukan oleh gubernur.
Begitu juga posisi gubernur, mendapatkan jabatan atas pilihan rakyatnya.
Lihat juga video “Kecelakaan Bus di Cipulir, Detik-detik Penyelamatan Sopir Bus Berlangsung Dramatis”. (youtube/poskota tv)
Harapannya, dengan dipilih langsung oleh rakyat, pejabat lebih amanah dengan berupaya maksimal menyejahterakan rakyat yang telah memilihnya.
Bukan menggunakan kekuasaannya untuk mengelabui rakyat demi memperkaya diri sendiri ataupun para "Sponsor".
Pejabat yang demikian selain tidak amanah, bisa disebut tidak kuat tahta.
Hati- hatilah dengan jabatan.
Tidak “kuat” segalanya, jangan mencoba.
Pitutur luhur mengajarkan “Ojo ketungkul marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman “ - Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh Kedudukan, Kebendaan dan Kepuasan duniawi. (Azisoko)