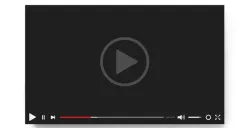BELAKANGAN ini kita sering menyaksikan fenomena di mana perdebatan yang seharusnya menjadi ajang tukar pikiran justru berakhir dengan hinaan dan makian. Kalimat-kalimat kasar sering kali menggantikan argumen rasional.
Fenomena ini seolah mencerminkan bahwa ketika logika tidak lagi menjadi tumpuan, perdebatan berubah menjadi ajang emosional tanpa akal sehat.
Ketika ruang publik, terutama yang ditonton oleh mahasiswa dan generasi muda, diisi dengan debat semacam ini, kita perlu bertanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan pendidikan karakter tokoh-tokoh kita?
Sebuah perdebatan yang sehat seharusnya didasarkan pada logika, bukti, dan analisis kritis.
Namun, belakangan ini, banyak tokoh publik justru memilih untuk meninggalkan logika dan beralih pada penghinaan pribadi.
Mengeluarkan kata-kata makian bukan hanya merusak suasana debat, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk menjawab argumen lawannya dengan rasional.
Ini adalah bentuk kekalahan yang lebih besar daripada sekadar kalah dalam adu argumen, ini adalah kekalahan karakter.
Ketika akal sehat tidak lagi menjadi pedoman, debat kehilangan makna. Tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi contoh intelektual malah memberikan contoh buruk.
Ini adalah tanda bahwa beberapa dari mereka tidak lagi menganggap penting keadaban dalam berbicara, apalagi saat berada di depan khalayak yang lebih luas.
Mahasiswa dan generasi muda menjadi saksi utama dari banyaknya perdebatan ini. Mereka sering kali menjadi penonton setia di media sosial atau acara debat televisi, menyerap setiap kata dan sikap yang diperlihatkan oleh para tokoh publik.
Ketika mereka melihat bahwa kata-kata kasar digunakan sebagai “senjata” dalam perdebatan, mereka bisa saja berpikir bahwa hal ini normal dan bahkan efektif dalam menghadapi perbedaan pendapat.
Padahal, pendidikan karakter mengajarkan pentingnya sikap hormat terhadap orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit atau penuh ketegangan.
Ketika mahasiswa menyaksikan tokoh-tokoh publik melontarkan hinaan, pesan yang tersampaikan adalah bahwa kekasaran bisa diterima dalam debat. Ini adalah kebalikan dari apa yang seharusnya mereka pelajari.
Pendidikan karakter adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup, dan tokoh publik memainkan peran besar dalam membentuknya.
Mereka memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap persepsi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
Ketika seorang tokoh publik kehilangan kendali dalam debat dan menggunakan kata-kata kasar, ia bukan hanya merusak reputasinya, tetapi juga merusak harapan akan debat yang sehat dan beretika.
Seorang tokoh yang baik seharusnya mampu berdebat dengan tenang dan berbasis logika, meski dalam situasi yang memancing emosi.
Menguasai emosi dan tetap berargumen dengan rasional menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, yang tidak kalah penting dari kecerdasan intelektual.
Tokoh publik harus menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan tidak hanya berdampak pada lawan debatnya, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat luas terhadap perbedaan pendapat.
Untuk mengembalikan debat pada jalurnya, kita perlu memprioritaskan logika dan etika dalam komunikasi publik.
Pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi harus lebih banyak menekankan pentingnya berdebat dengan argumen yang didasarkan pada data dan fakta, bukan emosi.
Selain itu, media juga memegang peran penting dalam menyaring dan menyajikan perdebatan yang berkualitas, bukan sekadar konten sensasional yang mengedepankan drama dan konflik.
Tokoh-tokoh publik perlu lebih sadar akan tanggung jawab moral mereka. Setiap kata yang mereka lontarkan memiliki dampak besar, terutama di era digital di mana segalanya dapat dengan cepat tersebar. (*)